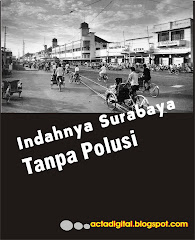Tuesday, February 06, 2007
UNTAIAN HARAP DI GREBEG SURO
Diposting oleh
ADAKHIL SANG PENAKLUK
di
8:07 AM
2
komentar
![]()
Label: FOTO ACTA
MOLOG SANG PENJAGA TRADISI REYOG
Harjokemun Al-Molog (mbah Molog), salah seorang pengrajin Reyog tertua yang masih tersisa di Ponorogo. Tampak ia sedang berpose di depan buah karyanya, Minggu (21/01).
Begitulah ungkapan perasaan Harjokemun Al-Molog (Mbah Molog), tatkala melihat kondisi kesenian Reyog saat ini pada Acta Surya. Menurutnya untuk menjaga kelestarian tradisinya patut dibutuhkan pemahaman tersendiri terhadap kesenian khas kota Ponorogo ini.
“Terutama pada pemahaman nilai-nilai jawa bagi para pengrajin maupun pecinta Reyog. Apalagi dalam membuatnya ada hitungan mistiknya dan saya sangat percaya akan itu,” imbuh lelaki yang kini berusia 83 tahun tersebut.
Melihat berbagai jerih payah Mbah Molog yang menekuni Reyog sejak usia 7 tahun. Baik dari segi penjagaan maupun pelestarian budaya Reyog. Sangat pantas jika dirinya mendapat piagam penghargaan Festival of American Folklife 1991 dari negeri Paman Sam, yang diberikan oleh the Smithsonian Institution.
“Kala itu saya sendiri yang datang ke Washington berkat undangan mereka,” aku Mbah Molog, sembari menunjukkan piagam tersebut yang terpasang di dinding rumahnya. Bukti lain jika Mbah Molog pantas disebut sebagai panjaga tradisi Reyog adalah terpampangnya dua buah piagam penghargaan lainnya di dinding rumahnya di jalan Tlutur 76 A Ponorogo.
Piagam tersebut adalah dari mantan Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Widarso Gondodiwirjo pada 18 Agustus 1978, sebagai “pembinaan seni tradisional daerah kabupaten Ponorogo dan pelatih penari Reyog”. Dan penghargaan dari mantan Gubernur Jatim Soelarso pada 31 Maret 1993, sebagai seniman seni rupa tradisional.
- naskah dan foto: M. Ridlo'i
Diposting oleh
ADAKHIL SANG PENAKLUK
di
7:49 AM
0
komentar
![]()
Label: SENI DAN BUDAYA
Sunday, February 04, 2007
REYOG : KISAH CINTA YANG TAK SAMPAI
Alunan nada-nada pelog dari kempul, ketipung, gong, kenong, angklung dan selompret (terompet tradisional) bertalu-talu. Irama tersebut terdengar mengiringi goyangan tarian Reyog khas Ponorogo.
Diawali tampilan penari jatilan dengan kuda tunggangannya. Warok tua dan warok muda pun masuk mengiringi para penari jatilan. Warok muda mengenakan baju dan celana serba hitam berkolor besar, ikat pinggang besar, keris dan ikat kepala hitam (gadung mondholan). Dagunya dipasangi jambang lebat, sedangkan dadanya digambari rambut. Warok tua tampil lebih kalem tanpa banyak riasan serta ikat kepala berwarna cokelat (modang).
Kemudian, disusul dengan masuknya Patih Bujang Ganong (muka merah dengan rambut acak-acakan di depan wajahnya) dan binatang Reyog Singo Barong dan Dhadhak Merak, yang dilanjut dengan masuknya Raja Kelana Sewandhana. Pertunjukkan terasa seru dan nuansa mistik mengiringi, serasa tak menggoyahkan nikmatnya penonton menyaksikan pertunjukkan tari Reyog.
Dalam lakon Reyog tersebut, menceritakan kisah cinta yang tidak kesampaian. Konon, penguasa kerajaan Bantarangin Prabu Kelana Swandana mengutus para pasukannya pimpinan Patih Bujang Ganong untuk melamar putri kerajaan Jenggala di Kediri, Sanga Langit.
Di tengah perjalanan rombongan disergap singa berbadan besar (Singa Barong). Kalah bertarung Bujang Ganong kembali. Prabu Klana Swandana akhirnya turun dan berhasil menaklukkan Singa Barong yang berubah menjadi Dadak Merak.
Sang putri mau disunting asalkan Prabu Kelana berkenan menciptakan seni pertunjukkan baru dengan melibatkan pasukan berkuda (Jathilan), meskipun pernikahan tidak jadi. Pasukan Prabu Klana membuat tarian arak-arakan perang diiringi tingkah sorak-sorai dan inilah yang dinamakan tari Reyog khas Ponorogo.
Sebelumnya, sebagian orang tak begitu paham jika dibalik nuansa mistik tampilan tari Reyog telah mengusung cerita asmara. “Selama ini pikiran saya dari tampilan Reyog itu menceritakan kisah misteri. Namun, ternyata Reyog itu ibarat drama percintaan,” celetuk Nani (31), yang kebetulan malam itu menyaksikan Festival Reyog Nasional XIII di Ponorogo, (19/1).
- naskah dan foto : M. Ridlo’i
Diposting oleh
ADAKHIL SANG PENAKLUK
di
7:59 AM
0
komentar
![]()
Label: SENI DAN BUDAYA
SUSUNAN REDAKSI
Ketua Stikosa-AWS
Pembina
Zainal Arifin Emka
Pimpinan Redaksi
M. Ridlo’I
Redaktur Senior
Hendri Dwi Wahyudi
Redaktur Pelaksana
Guntur Irianto P, Windy Goestiana dan Dinar Pranesti
Redaktur Foto
Wahyu Triatmodjo
Koordinator Liputan
Andrian Saputri
Staf Redaksi
Dimas Prasaja, Arief Armansyah, Shiska Pradibka, Chadijah Mukadar, Eva Mayasari Hidayanti, Eufrata Nuraini, Kurnia Fajrina, Desty CP.
Fotografer
Wahyu Agus S dan Akbar Insani.
Artistik
Syarifuddin Darwis dan Masrul Fajrin.
Humas dan Marketing
Djarot Budi P dan Wirawan Choiron.
Alamat Redaksi
Kampus Stikosa-AWS
Jl. Nginden Intan Timur I/18 Surabaya.
Telp : 081 703 131 213, 031 71 388 970
E-mail : actasuryamedia@yahoo.com
Homepage : http://actadigital.blogspot.com
Wartawan dan fotografer Acta Surya selalu membawa tanda pengenal dalam menjalankan tugas liputannya dan tidak diperkenankan menerima atau meminta apapun dari narasumber.
Diposting oleh
ADAKHIL SANG PENAKLUK
di
7:56 AM
0
komentar
![]()
Label: DARI KAMI
UNTAIAN HARAP DI GREBEG SURO
 Perilaku masyarakat Jawa Timur yang percaya untuk meneruskan tradisi leluhurnya masih begitu melekat. Grebeg Suro sebagai buktinya, kebanyakan mereka tak melewatkannya demi untaian harap berkah leluhur.
Perilaku masyarakat Jawa Timur yang percaya untuk meneruskan tradisi leluhurnya masih begitu melekat. Grebeg Suro sebagai buktinya, kebanyakan mereka tak melewatkannya demi untaian harap berkah leluhur.Tahun 2007 ini, hampir di setiap kota di Jawa Timur yang masih kental nuansa budaya Jawa merayakan grebeg suro. Seperti di Mojokerto, Nganjuk, Malang, Tulungangung, Ponorogo dan lain sebagainya.
Dibanding dengan peringatan Grebeg Suro di berbagai kota, peringatan di Ponorogo sedikit berbeda. Di tempat ini ada Pesta Rakyat Reyog Ponorogo yang digelar secara massal, pawai kota, kirab pusaka, begadang semalam suntuk atau pesta rakyat dan larung sesaji di Danau Ngebel. Semua dilaksanakan dalam satu rangkaian pesta.
Untuk mengenang sejarah leluhur dari kota Reyog (penulisan yang kini digunakan, Red) dan semata mengharap berkah Suro-an. Masyarakat di kabupaten yang memiliki luas wilayah 1.402 kilometer persegi ini mulai pagi hingga sore, Jum’at (19/1) lalu, memadati makam salah seorang leluhur juga selaku Adipati I kota Reyog Raden Batoro Katong, yang terletak di kelurahan Jenangan, kecamatan Setono Ponorogo.
Selain berdo’a, kehadiran warga juga untuk melakukan kirab tiga buah replika pusaka Batoro Katong. Yaitu Tumbak Tunggul Wulung, Payung Tunggul Naga dan Cindhi Puspito. Ketiga pusaka di kirab oleh pasukan pembawa pusaka yang sebelumnya mendapat bekal spiritual dari delapan orang dari Yayasan Para Psikologi Semesta (YPS) di lokasi makam.
Pusaka telah diserahterimakan. Kirab dan pawai pun dimulai. Jalanan kota lama (kelurahan Setono) hingga ke kota baru (kantor kabupaten) penuh sesak warga setempat. “Kami melakukan kirab dan pawai untuk tapak tilas sejarah leluhur, yakni sebagai pertanda perpindahan pemerintahan yang kala itu pusatnya ada di tempat ini (pendopo makam Batoro Katong),” ungkap juru kunci makam tersebut Sunardi (56).
Hujan deras yang membasahi jantung kota malam itu, seakan tak menghalangi niatan ribuan orang yang sedang menanti perayaan malam pergantian tahun 1427 H menjadi 1428 H. Mulai komedi putar dan para pedagang yang menjajakan barang dagangannya pada pengunjung, seakan bersaing dengan warga yang memanfaatkan momentum ini.
Tak hanya itu, penutupan festival Reyog Nasional XIII juga berlangsung di Alun-Alun Kota Ponorogo. Dengan menyajikan suguhan tarian Reyog khas Ponorogo, yang dilanjut dengan pesta kembang api pada tengah malamnya. Menandai pergantian tahun jawa 1939 berganti menjadi 1940..
Festival Reyog Ponorogo tahun ini sendiri diikuti 31 kelompok Reyog yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mulai Lampung Propinsi Lampung, Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kutai Kertanegara, Jawa Tengah dan Ponorogo.
“Bangga sekali, melihat keantusian berbagai daerah dalam menyemarakkan acara ini, sekaligus sebagai bukti kesenian reyog masih pantas diunggulkan,” kata Bupati Ponorogo Muhadi Suyono dalam sambutannya.
Acara Puncaknya, Sabtu (20/1) pagi masyarakat berduyun-duyun memadati tepian telaga Ngebel yang berjarak 25 kilometer sebelah timur pusat Kota Ponorogo. Sebagai wujud persembahan untaian harap pada leluhur dan beriring keheningan do’a kepada Sang Kuasa, mereka lakukan larung risalah do’a (berupa kotak dan tumpeng raksasa terbuat dari ketan merah).
Sebelumnya, tumpeng dan kotak do’a tersebut diarak mengelilingi telaga, dengan memakan waktu satu jam. Setelah diarak dan sampai di telaga, keduanya dinaikkan perahu bambu dan dilarung hingga ke tengah telaga dengan bantuan dorongan seseorang berpakaian serba hitam. Sayup-sayup musik Reyog terdengar bertalu-talu, do’a pun terpanjatkan.
“Ini semua dilakukan untuk ngeruwat (kirim do’a) kepada yang Kuasa dan tentunya mengharap berkah dari leluhur,” tutur Umi Lestari (50), warga Nglingi Ngebel.
- Naskah dan foto: M. Ridlo’i
Diposting oleh
ADAKHIL SANG PENAKLUK
di
7:34 AM
0
komentar
![]()
Label: SENI DAN BUDAYA
ACTA SURYA ADALAH ............
Berdirinya kampus Akademi Wartawan Surabaya (AWS) pada tahun 1964, merupakan cerminan daripada lahirnya media internal kampus tersebut dengan nama “Acta Surya”. Konon, media ini didirikan atas inisiatif beberapa mahasiswa sebagai bentuk penyikapan terhadap berbagai peristiwa yang terjadi pada waktu itu.
Ya, Amak Syariduddin adalah pendiri sekaligus pemimpin redaksi pertama Acta Surya. Bersama teman-teman seangkatannya, dia merias wajah media ini menjadi sebuah media internal kampus yang disegani di Surabaya.
Asal kata Acta Surya
Acta berasal dari bahasa Yunani “Acta Diorna”. Yaitu sebuah catatan atau berita. Sedangkan Surya adalah singkatan dari “Surabaya”. Jadi kalau digabungkan berarti “Sebuah Catatan atau Berita Surabaya”.
Acta Surya sempat mengalami masa kejayaannya. Misalnya di tahun 1998, media kampus yang memiliki ijin penerbitan 17 Maret 1966 ini, merupakan simbol dari pergerakan mahasiswa di Surabaya dalam upaya pelengseran mantan Presiden Soeharto. Nah, itulah sekelumit kisah manis tentang media kampus ini.
Pergantian waktu tampaknya juga berdampak pada aktivitas Acta Surya saat ini. Harusnya, dengan potensi yang dimiliki organisasi penerbitan ini tentu gerak langkahnya semakin maju seiring perkembangan masa dan tekhnologi. Ironisnya, Acta Surya kian terpuruk dan hanya bingung mengurusi ‘tubuhya’ yang tidak konsisten. Hal ini terlihat dari kualitas terbitan yang pas-pasan dan jerohan manajemennya yang kalang kabut selama 2-3 tahun terakhir ini. Mungkin karena biaya produksi diambil dari iuran mahasiswa yang sangat minim, sedang pihak akademik juga tak mau ambil pusing untuk biayai penerbitan Acta surya. Padahal media ini dianggap sebagai ‘Humas’-nya kampus yang notabene markasnya wartawan ini, bahkan dulu dianggap sebagai karakter khasnya kampus ini. Yah, mungkin inilah tantangan yang harus dihadapi. Tentunya dengan banyak strategi yang harus dipersiapkan dengan matang.
Melihat kenyataan di atas, segenap pengurus redaksi berencana melakukan inovasi-inovasi untuk mengembalikan pamor Acta Surya yang kian hilang ditelan zaman. Konkritnya, redaksi telah membuat lahan baru untuk pembelajaran menulis bagi anggota barunya berupa mading (Acta Surya On the Board), mengefektifkan kembali penerbitan majalah Acta Surya serta memperbaiki jalinan hubungan baik secara emosional dan dalam konteks dunia kerja dengan para alumni dan media kampus lain. Dan satu hal yang pasti, kegiatan off print akan disemarakkan lagi guna menambah wawasan bagi anggota tercinta Acta Surya.
Diposting oleh
ADAKHIL SANG PENAKLUK
di
7:11 AM
1 komentar
![]()
Label: DARI KAMI